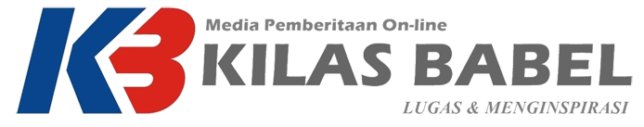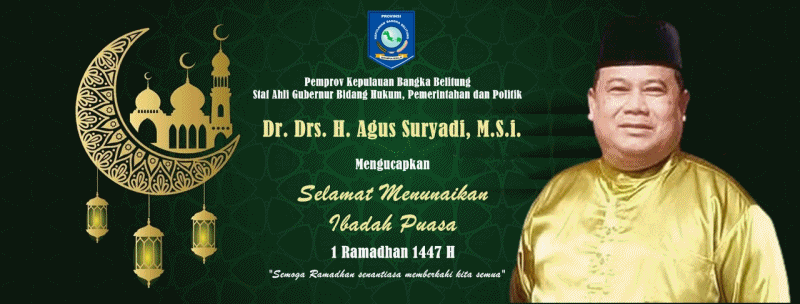Oleh:
Rahmi
(Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pahlawan 12)
KILASBABEL.COM – Di balik tumpukan sampah rumah tangga, tersimpan potensi ekonomi dan solusi lingkungan. Sayangnya, tak semua warga menyadari hal itu. Program bank sampah yang digagas pemerintah sebagai jalan keluar masih belum mendapat sambutan luas. Di sinilah peran administrasi publik diuji, mampukah ia menjawab tantangan perubahan perilaku masyarakat?
Bank sampah bukan hal baru. Sejak diperkenalkan lebih dari satu deka delalu, konsep ini telah berkembang di berbagai daerah. Warga diajak memilah sampah, lalu menyetorkannya ke bank sampah seperti menabung. Sampah yang memiliki nilai jual, seperti botol plastik, kertas, dan logam, dicatat dan ditukar dengan uang, sembako, bahkan pulsa.
Namun, realitas di lapangan berkata lain. Di banyak tempat, partisipasi warga masih rendah. Di Kabupaten Bangka, misalnya, beberapa unit bank sampah terbentuk tetapi sepi aktivitas. Banyak warga belum terbiasa memilah sampah, apalagi menyetor rutin ke bank sampah.
Kenapa Partisipasi Rendah?
Minimnya sosialisasi, kurangnya insentif, hingga anggapan bahwa memilah sampah merepotkan menjadi alasan umum. Padahal, jika dikelola dengan prinsip-prinsip administrasi publik yang baik, bank sampah bisa menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
Menurut pakar administrasi publik, program seperti bank sampah hanya akan berhasil jika pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai fasilitator dan komunikator yang baik.
Prinsip Administrasi Publik yang Bisa Mengubah Keadaan
1. Partisipatif dan Terbuka
Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi aktif masyarakat. Bukan sekadar mengajak, tapi juga mendengar. Apa yang membuat warga enggan terlibat? Apa yang bisa membuat mereka tertarik? Dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, hingga kelompok ibu-ibu PKK, pesan soal pentingnya bank sampah bisa sampai ke akar rumput.
2. Transparansi Membangun Kepercayaan
Warga akan tertarik bila sistemnya jelas. Misalnya, berapa nilai jual sampah, bagaimana catatan tabungan dibuat, dan ke mana uang hasil penjualan sampah digunakan. Semakin transparan, semakin besar kepercayaan publik.
3. Cepat dan Responsif
Respon cepat terhadap keluhan warga bisa menjadi kunci. Jika tempat setor terlalu jauh, atau jadwal tidak sesuai, warga pasti enggan. Solusinya bisa sederhana: tambah titik setor, sesuaikan jadwal, atau bentuk petugas jemput sampah. Responsivitas adalah bagian dari pelayanan publik yang humanis.
4. Efisien dan Terdigitalisasi
Di era digital, pencatatan manual bukan lagi satu-satunya pilihan. Beberapa daerah mulai mengembangkan aplikasi bank sampah. Warga bisa melihat saldo sampahnya melalui ponsel. Mudah, cepat, dan menarik bagi generasi muda.
5. Desentralisasi Pengelolaan
Bank sampah tak bisa dikendalikan hanya dari atas. Perlu ada pelibatan langsung dari kelurahan, desa, bahkan RT/RW. Ketika pengelola ada di lingkungan sendiri, pendekatan yang dilakukan jadi lebih sesuai dengan karakter warganya.
Saatnya Pemerintah dan Warga Bergerak Bersama
Bank sampah bukan hanya program lingkungan. Ia adalah cerminan budaya baru: peduli, tertib, dan berdaya. Tapi budaya tidak tumbuh dalam sehari. Ia dibentuk oleh kebijakan yang mendidik, pelayanan yang memudahkan, dan komunikasi yang membangun.
Pemerintah daerah punya pekerjaan rumah besar, membangun kepercayaan, membuka partisipasi, dan terus mengawal keberlanjutan. Sementara warga, sudah saatnya tak hanya menunggu program datang, tapi ikut menghidupkannya. Karena soal sampah, bukan hanya urusan pemerintah. Ini soal kita bersama. (*)