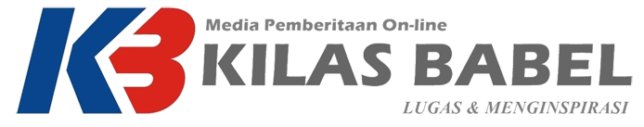Oleh :
Prof. Muhadam
(Ketua Harian MIPI/Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN)
Tiap kali perhelatan pemilu, kita disuguhi perjanjian baru oleh para calon pemimpin. Bila incumbent, perjanjian lama direvitalisasi, lalu diperpanjang lewat kampanye. Tentu semua dengan alasan ideal, demi kemaslahatan orang banyak, kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem, bentuk, dan style apapun, pada akhirnya semua rezim lewat kontrak sosial yang direkonstruksi berulangkali pada ujungnya tiba di muara kemakmuran. Kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia, bukan semata kelompok, golongan, ataupun oligarki.
Distribusi kemakmuran idealnya dimulai dari yang paling banyak dan lemah. Dalam struktur sosial mereka di piramida terbawah. Contohnya, kurang lebih 65% kelas sudra itu mendapat kucuran lewat rupa-rupa program, sekaligus jaring pengaman sosial (social safety).
Membuncitnya kelas menengah kebawah membuat alokasi anggaran sebanyak apapun tetap saja tiba ditelapak tangan dengan jumlah minimal. Kendati faktanya mereka telah menggadai suara saat pesta demokrasi dengan harga pasar minimal antara 100 sampai dengan 300 ribu rupiah persuara.
Dalam demokrasi dengan basis peserta tuna didik, suara rakyat dibeli putus. Tak ada konsekuensi setelah terpilih. Suara tak dapat dikontrol hingga bursa demokrasi dibuka kembali secara periodik, 5 tahun sekali. Para penadah dan calo suara merupakan mafia demokrasi yang tumbuh subur di masa pemilu.
Ironisnya bagian terbesar dari kue kesejahteraan itu justru mengalir deras pada elit yang jumlahnya dapat dihitung jari. Ditambah koordinator pemengaruh (influenzer), pendengung (buzzer), hingga timses. Mereka mendapat kemewahan dan privilage. Boleh pilih sebagai dirut, komut, maupun posisi strategis lainnya.
Selebihnya mereka yang mampu menyenangkan atasan. Duduk sebagai orang dalam, kata Indraswara (2025). Punya keahlian menjilat. Bila menjilat saja anda tak kompeten, bagaimana mungkin menjadi bagian dari kekuasaan, sindir Jubir Istana Hasbi (2025). Sejak purba, penjilat adalah profesi biasa dan unik dalam politik.
Dalam konteks itulah keadilan tak menemukan timbangan. Yang banyak dan lemah mendapat sedikit, sementara yang sedikit dan kuat mendapat banyak. Esensi keadilan substantif tenggelam dengan argumen keadilan proporsional. Eksesnya sumber kesejahteraan banjir di hulu, tapi ibarat botol, mengecil dan menetes saat tiba di muara.
Gambaran itu mudah dikonfirmasi. Eksploitasi sumber daya alam mencapai angka fantastis, tapi ketika sampai dimulut 280 juta penduduk tinggal recehan. Numeratifnya lihat komposisi APBN, dimana kontribusi SDA hanya menyumbang 7% dari porsi 17% non pajak.
Pajak sendiri disokong kaum papa hingga capai 83%. Tapi bagian mereka tak signifikan memutus problem dirinya sendiri. Di situ ketimpangan keadilan terlihat. Kekayaan negara belum menyentuh bagian yang secara faktual menjadi pokok urusan negara untuk disejahterakan. (*)